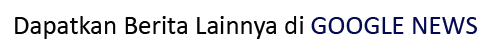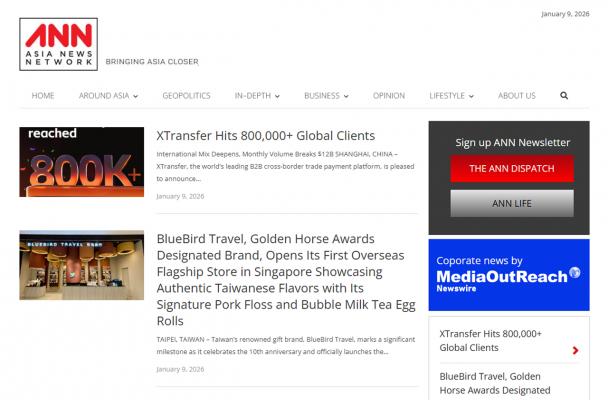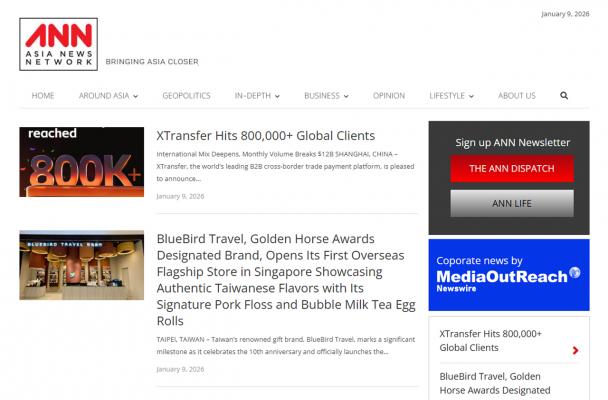- Home
- Ruang Opini
- Sumpur Kudus: Dapur yang Hidup dari Ladang dan Alam
Sumpur Kudus: Dapur yang Hidup dari Ladang dan Alam
Oleh: Ari Yuliasril
Jumat, 17 Oktober 2025 | 13:12
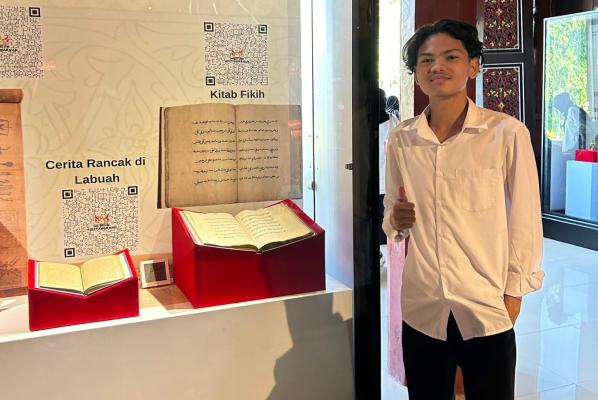
JIKA KAMU berkunjung ke Kabupaten Sijunjung, jangan
lewatkan satu nagari tua yang masih hidup dalam aroma masa lalu, Nagari
Sumpur Kudus. Di sini, asap tipis dari tungku kayu masih naik perlahan
setiap pagi, bercampur dengan wangi santan, cabai, dan serai yang
menandai denyut kehidupan masyarakatnya.
Dari
luar, Sumpur Kudus tampak seperti nagari lain di Ranah Minang, sawah
bertingkat, rumah gadang berdiri anggun, dan anak-anak bermain di
halaman surau. Namun, di balik kesederhanaan itu, tersembunyi
dapur-dapur yang menyimpan warisan kuliner luar biasa, kuliner yang
bukan hanya soal rasa, tetapi juga kisah tentang bagaimana manusia
belajar dari alam dan menghormati setiap anugerahnya.
Sumpur
Kudus terkenal karena keberaniannya menjaga tradisi kuliner yang unik,
Rendang Belalang. Bagi sebagian orang, belalang mungkin tak lebih dari
serangga yang beterbangan di ladang. Tapi bagi masyarakat Sumpur Kudus,
belalang adalah berkah, sumber protein alami yang bisa diolah menjadi
santapan istimewa.
Prosesnya
tidak main-main. Belalang dikumpulkan dari ladang pada musim tertentu,
lalu digoreng hingga kering agar renyah. Setelah itu dimasak dengan
santan, cabai, serai, dan lengkuas, rempah dasar masakan Minang, hingga
kuahnya surut dan bumbunya meresap sempurna.
Hasilnya'
Gurih, pedas, dan renyah. Teksturnya unik, aromanya kuat, dan cita
rasanya menggugah rasa penasaran siapa pun yang berani mencoba.
“Kami
belajar dari alam,” kata Mak Yanti, seorang ibu rumah tangga yang sudah
puluhan tahun mengolah belalang menjadi rendang. “Kalau di sawah banyak
belalang, jangan dibuang. Alam memberi tanda, berarti ada rezeki di
sana.”
Bagi masyarakat
Sumpur Kudus, rendang belalang bukan sekadar kuliner ekstrem, tetapi
cermin filosofi hidup Minangkabau, bagaimana manusia hidup seimbang
dengan alam. Mereka tidak serakah, tidak mengambil lebih dari yang
dibutuhkan, tetapi juga tidak membiarkan potensi alam terbuang
percuma.Inilah wajah asli kearifan lokal, sederhana, tapi penuh makna.
Belalang
di Sumpur Kudus tidak hanya dijadikan rendang. Ia juga sering diolah
menjadi sambal belalang, makanan rumahan yang sederhana tapi menggugah
selera. Caranya, belalang digoreng garing lalu ditumbuk kasar bersama
cabai merah, bawang, dan sedikit garam. Teksturnya renyah, pedasnya pas,
dan aromanya khas. Makan nasi hangat dengan sambal belalang, kata orang
sini, bisa membuat “lupo diri”, lupa berhenti makan.
Selain
belalang, ada pula Kalio Joghiang, olahan jengkol khas Sumpur Kudus.
Dalam bahasa setempat, jengkol disebut joghiang. Dimasak dengan santan
kental, daun salam, cabai, dan rempah, kalio ini tak sampai kering
seperti rendang, kuahnya masih kental, bumbunya melekat lembut di lidah.
Bagi
orang luar, jengkol sering dianggap bahan kelas bawah, tapi di Sumpur
Kudus, jengkol naik derajat. Ia dihidangkan di pesta adat, jamuan tamu,
bahkan jadi menu utama dalam alek nagari.
Kebijaksanaan masyarakat tampak jelas di sini, tidak ada bahan yang hina di dapur yang penuh cinta.
Jika
kamu berkunjung ke Sumpur Kudus saat ada acara adat, aroma harum bambu
panggang akan langsung menyambutmu. Itu tanda bahwa warga sedang membuat
Lamang Tongkat, penganan khas dari beras ketan yang dimasak di dalam
bambu panjang di atas bara api.
Prosesnya
membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bara api harus dijaga agar
panasnya stabil, dan bambu harus diputar perlahan supaya matangnya
merata. Saat bambu dibuka, aroma wangi ketan yang berpadu dengan asap
kayu langsung menyeruak. Rasanya gurih, lembut, dan sedikit berasap,
cita rasa yang tak bisa ditiru oven modern.
Sementara
itu, di sisi lain dapur, ibu-ibu menyiapkan Godok Obuih, kue lembut
dari tepung beras, santan, dan gula aren. Adonannya sederhana, tapi cara
memasaknya tetap tradisional, direbus pelan hingga matang, menghasilkan
tekstur legit dan rasa manis alami yang pas di lidah.
Biasanya
godok obuih disajikan saat sore hari, ditemani secangkir kopi hitam
atau teh talua hangat. Makanan ini menjadi simbol ketenangan dan
kebersamaan, mengingatkan orang bahwa kebahagiaan sering lahir dari
hal-hal yang sederhana.
“Kalau
makan lamang, kita ingat bambu,” ujar Pak Rusdi, tokoh adat setempat.
“Bambu itu kuat karena kosong di dalam. Artinya, orang besar harus
rendah hati.” Begitulah, bahkan sepotong lamang pun bisa menjadi
pelajaran hidup.
Di
banyak daerah, dapur hanya tempat memasak. Tapi di Sumpur Kudus, dapur
adalah jantung kehidupan. Di sanalah perempuan saling berbagi kabar,
anak-anak belajar menghormati orang tua, dan laki-laki ikut membantu
menyiapkan bahan saat pesta adat.
Dapur
di nagari ini juga menjadi ruang pendidikan budaya. Resep diturunkan
lewat pengalaman, bukan tulisan. Anak-anak belajar dengan melihat dan
membantu. Sambil mengulek cabai atau memarut kelapa, mereka menyerap
nilai tentang gotong royong, kesabaran, dan cinta pada tanah sendiri.
Bagi
masyarakat Sumpur Kudus, memasak bukan pekerjaan domestik, tetapi
tindakan budaya, cara menjaga identitas dan merawat hubungan dengan
alam.
Namun, seperti
banyak nagari tua lainnya, Sumpur Kudus kini menghadapi tantangan.
Modernisasi membuat sebagian anak muda lebih mengenal mi instan
ketimbang godok obuih, lebih akrab dengan fast food daripada kalio
joghiang.
Beberapa
generasi muda mulai melupakan bagaimana menyalakan tungku, memilih
santan instan ketimbang memeras kelapa sendiri. Di sinilah pentingnya
peran keluarga dan pemerintah nagari untuk menghidupkan kembali dapur
tradisional sebagai ruang belajar dan kebanggaan lokal.
Karena
sejatinya, kuliner bukan hanya urusan perut, tapi juga urusan
identitas. Di Sumpur Kudus, setiap rendang belalang yang dimasak, setiap
lamang yang dibakar, adalah doa agar hubungan antara manusia dan alam
tetap harmonis.
Sumpur
Kudus mengajarkan kita bahwa tradisi tidak selalu harus megah. Ia bisa
hadir dalam wujud paling sederhana, belalang di kuali, jengkol di kalio,
atau ketan dalam bambu.
Di nagari ini, dapur
adalah sejarah yang hidup, tempat di mana rasa, doa, dan kearifan
menyatu dalam satu aroma yang tak pernah pudar.
BERITA LAINNYA

Kamis, 16 Oktober 2025 | 10:17

Jumat, 17 Juni 2022 | 23:01