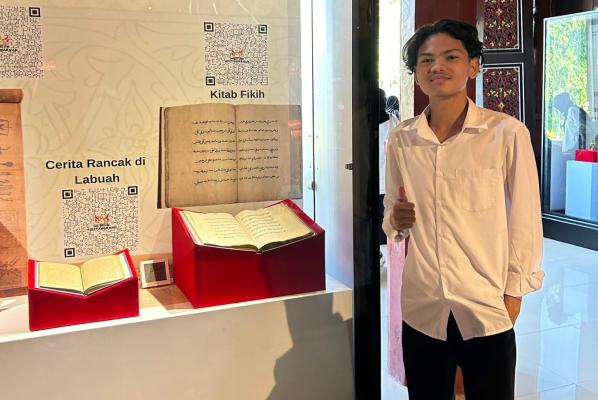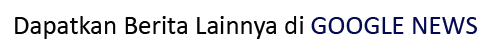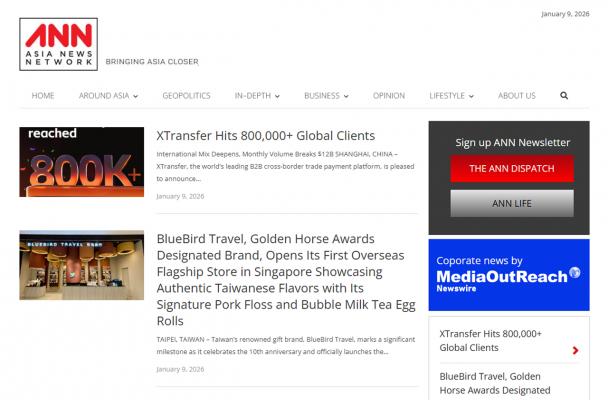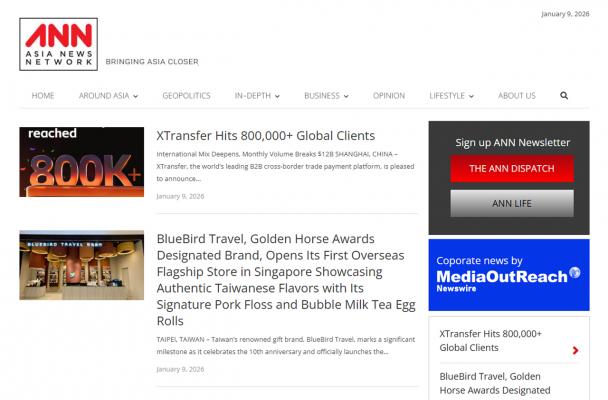- Home
- Ruang Opini
- Saat Krisis Iklim Menuntut Perubahan Sistem, Bukan Sekadar Perilaku
Saat Krisis Iklim Menuntut Perubahan Sistem, Bukan Sekadar Perilaku
Oleh: T.H. Hari Sucahyo*

Siapa pun yang hari ini terlibat dalam isu krisis iklim dan ekologi tahu bahwa kita telah melewati titik di mana “meningkatkan kesadaran” masih bisa dianggap strategi utama. Dunia tidak kekurangan pengetahuan tentang kehancuran yang sedang terjadi. Fakta-fakta sudah tersedia di mana-mana: emisi karbon terus meningkat, ekosistem laut dan darat runtuh, hutan-hutan tropis terbakar habis, suhu global naik dengan kecepatan yang melampaui prediksi model ilmiah, dan bencana ekstrem menjadi keseharian.
Kita semua tahu, setidaknya secara rasional bahwa bumi sedang terbakar. Dan kita juga tahu bahwa tindakan individual seperti mengurangi penggunaan sedotan plastik, mengganti lampu pijar dengan LED, atau lebih sering bersepeda ke kantor, tidak akan membalikkan arah sejarah ini.
Kesadaran publik memang pernah menjadi titik awal yang penting. Dua dekade lalu, gerakan lingkungan hidup masih berjuang menembus dinding ketidaktahuan massal.
Saat itu, menampilkan foto beruang kutub yang terjebak di bongkahan es terakhir di Kutub Utara atau memaparkan grafik peningkatan suhu global masih bisa mengguncang hati dan mengubah perilaku. Namun hari ini, kesadaran bukanlah barang langka. Ia justru telah menjadi semacam komoditas baru; diproduksi, dikonsumsi, dan dijadikan bahan kampanye oleh korporasi maupun pemerintah, tanpa benar-benar mengubah struktur kekuasaan dan ekonomi yang melahirkan krisis itu.
Profesor Jason Hickel, seorang ekonom dan pemikir pasca-pertumbuhan, baru-baru ini menulis bahwa banyak gerakan iklim modern terjebak dalam lingkaran yang sama: terlalu fokus pada membangun kesadaran, seolah-olah masyarakat hanya butuh lebih banyak informasi untuk bertindak. Padahal, kata Hickel, masalah kita bukan kurangnya pengetahuan, melainkan kurangnya kekuasaan untuk menantang sistem yang berakar dalam logika pertumbuhan tanpa batas. Ia menyebut bahwa wacana kesadaran sering kali berfungsi sebagai “katup pengaman moral” yang memberi rasa lega bahwa kita sedang melakukan sesuatu, padahal yang sebenarnya kita lakukan hanyalah memperpanjang rasa bersalah tanpa arah politik yang jelas.
Krisis iklim adalah hasil dari struktur ekonomi global yang dibangun di atas ekstraksi: pengambilan sumber daya alam tanpa batas, eksploitasi tenaga kerja, dan akumulasi kapital yang tak mengenal henti. Dengan kata lain, krisis ini bukan hasil dari “kesalahan kolektif manusia” sebagaimana sering digambarkan, melainkan konsekuensi langsung dari sistem yang menguntungkan segelintir pihak dengan mengorbankan banyak yang lain. Karena itu, solusi personal seperti diet karbon atau hidup minimalis, betapapun baik niatnya, tidak akan pernah cukup untuk menandingi kekuatan politik dan finansial dari sistem yang mengakar ini.
Dalam budaya populer, gagasan tentang tanggung jawab individual tetap mendominasi. Kita dijejali pesan bahwa “setiap tindakan kecil berarti,” atau bahwa “perubahan besar dimulai dari diri sendiri.” Pesan-pesan itu tampak positif, tapi secara politis menyesatkan. Ia mengalihkan perhatian dari pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang sebenarnya bertanggung jawab' Siapa yang memegang kendali atas arah produksi energi, transportasi global, dan rantai pasok industri yang memuntahkan emisi ke atmosfer'
Dalam logika kapitalisme global, tanggung jawab selalu dipersonalisasi. Perusahaan minyak terbesar di dunia, misalnya, menghabiskan puluhan juta dolar untuk mempromosikan istilah “jejak karbon pribadi”, bukan tanpa alasan. Dengan menggeser wacana dari “jejak karbon korporasi” menjadi “jejak karbon individu,” mereka berhasil membuat masyarakat sibuk menghitung dampak diri sendiri, sambil menutupi fakta bahwa 100 perusahaan bertanggung jawab atas lebih dari 70% emisi global sejak 1988. Kesadaran, dalam konteks ini, menjadi senjata ideologis. Ia menenangkan hati, memberi rasa kendali, tapi sekaligus menumpulkan potensi perlawanan.
Kita seolah-olah hidup dalam paradoks besar: di satu sisi, lebih banyak orang daripada sebelumnya memahami bahaya krisis iklim; di sisi lain, emisi global justru terus meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran tidak otomatis berujung pada perubahan. Antara tahu dan bertindak terbentang jurang besar yang bernama kekuasaan. Selama struktur politik dan ekonomi tidak diubah, kesadaran hanya akan menjadi cermin tempat kita memandangi keputusasaan sendiri.
Gerakan iklim global kini menghadapi dilema eksistensial: bagaimana bergerak melampaui paradigma kesadaran menuju transformasi politik yang nyata. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak aktivis muda mulai menyadari bahwa aksi simbolik seperti mogok sekolah atau kampanye media sosial, meski penting sebagai bentuk ekspresi moral, tidak cukup mengguncang sistem. Mereka mulai berbicara tentang keadilan iklim—tentang hubungan antara kapitalisme, kolonialisme, dan kerusakan lingkungan. Mereka memahami bahwa krisis ini tidak netral: ia menimpa sebagian dunia jauh lebih parah daripada yang lain, mengikuti jejak ketimpangan global yang sama dengan masa kolonial.
Bahkan wacana keadilan iklim pun kini terancam terkooptasi. Pemerintah dan lembaga internasional dengan cepat mengadopsi istilah itu dalam dokumen-dokumen resmi, mengubahnya menjadi jargon teknokratis tanpa isi. Sementara di lapangan, komunitas adat yang mempertahankan hutan dari perusahaan tambang justru dikriminalisasi; petani yang melawan proyek energi “hijau” kehilangan tanahnya atas nama transisi. Ironinya, ekonomi hijau versi korporasi kini menjadi wajah baru dari eksploitasi lama: ekstraksi sumber daya untuk memproduksi baterai dan panel surya yang dijual ke pasar global, dengan biaya sosial dan ekologis yang tetap ditanggung oleh Selatan dunia.
Apa yang hilang dari gerakan iklim hari ini, sebagaimana dikatakan Hickel, adalah imajinasi politik yang berani. Kita terlalu lama menganggap bahwa solusi harus datang dari inovasi teknologi atau efisiensi energi. Padahal, teknologi tanpa perubahan sistem hanyalah tambal sulam. Peningkatan efisiensi energi, misalnya, sering kali justru mempercepat konsumsi total—sebuah paradoks yang dikenal sebagai “efek rebound.” Setiap kali kita menemukan cara lebih murah atau lebih efisien untuk memproduksi sesuatu, pasar memperluas konsumsi barang itu hingga akhirnya emisi tetap meningkat. Dengan kata lain, kita tidak bisa menyelesaikan krisis dengan logika yang sama yang menciptakannya.
Hickel mengusulkan paradigma pasca-pertumbuhan, sebuah sistem ekonomi yang tidak lagi bergantung pada peningkatan PDB sebagai ukuran kesejahteraan. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara kaya tidak lagi berarti peningkatan kesejahteraan, melainkan hanya memperlebar kesenjangan dan mempercepat degradasi ekologis. Alih-alih mengejar pertumbuhan tanpa batas, masyarakat perlu beralih pada model distribusi yang adil: memotong produksi yang tidak perlu, mengurangi jam kerja, membangun sistem publik yang kuat, dan menata ulang hubungan manusia dengan alam.
Ide ini terdengar radikal bagi banyak orang, terutama bagi para pembuat kebijakan yang masih terjebak dalam paradigma lama. Mereka lebih nyaman berbicara tentang “pertumbuhan hijau,” seolah-olah kita bisa terus memperluas ekonomi sambil menurunkan emisi secara bersamaan. Padahal, bukti empiris menunjukkan bahwa decoupling absolut antara pertumbuhan dan emisi hampir mustahil dicapai pada skala global. Kita tidak bisa menanam pohon sambil terus menebang hutan di tempat lain dan menyebutnya “net zero.”
Masalahnya, narasi pasca-pertumbuhan menantang fondasi ideologis dunia modern: gagasan bahwa kemajuan selalu identik dengan ekspansi ekonomi. Itulah sebabnya ia sering dipinggirkan, dicemooh, atau dianggap utopis. Tetapi bukankah setiap perubahan besar dalam sejarah manusia selalu dimulai dari gagasan yang dianggap utopis' Mengakhiri perbudakan dulu juga tampak mustahil; memberikan hak pilih kepada perempuan pernah dianggap mengancam tatanan sosial. Kini, mempertanyakan pertumbuhan ekonomi mungkin terasa menakutkan, tapi barangkali di situlah satu-satunya jalan keluar dari spiral kehancuran ekologis yang kita jalani.
Kesadaran tanpa aksi struktural akhirnya hanya melahirkan keputusasaan baru. Kita hidup di era “doomscrolling,” di mana informasi tentang kehancuran planet mengalir tanpa henti di layar ponsel. Setiap gambar kebakaran hutan, banjir bandang, atau suhu ekstrem menambah rasa bersalah, tapi tidak memberikan arah. Orang-orang menjadi lelah secara moral. Mereka tahu dunia sedang runtuh, tapi merasa tak berdaya untuk mengubahnya. Dan di saat seperti itu, industri politik dan korporasi terus melangkah dengan tenang, membungkus bisnis lama dalam narasi hijau, menanam citra bahwa mereka bagian dari solusi.
Yang kita butuhkan kini bukan lagi sekadar kesadaran, melainkan keberanian untuk menantang struktur yang menindas. Bukan hanya perubahan perilaku, tetapi perubahan sistem. Gerakan iklim harus berani menjadi gerakan politik, bukan sekadar moral. Ia harus menuntut pengakhiran rezim ekstraksi, nasionalisasi sumber daya energi, pembatasan kekuasaan korporasi, dan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan, bukan pertumbuhan. Ia harus berpihak pada mereka yang paling terdampak: masyarakat adat, petani kecil, nelayan, buruh migran. Mereka yang selama ini menanggung beban krisis tanpa pernah menikmati manfaat dari sistem yang menciptakannya.
Kesadaran hanyalah langkah pertama, tapi langkah itu sudah terlalu lama kita injak tanpa bergerak maju. Sekarang adalah waktu untuk berpindah dari pengetahuan menuju keberanian, dari rasa bersalah menuju tindakan, dari kesadaran menuju perubahan yang berakar. Hickel menulis bahwa masa depan yang berkelanjutan bukan sekadar dunia dengan teknologi yang lebih bersih, melainkan dunia yang lebih adil. Dunia di mana manusia hidup dalam batas ekologi, bukan karena takut pada kehancuran, tapi karena memilih kesalingtergantungan sebagai dasar kehidupan.
Barangkali, di masa depan, kita akan menertawakan betapa lamanya kita terjebak dalam ilusi bahwa kesadaran saja sudah cukup. Seperti orang yang terus memandangi peta tanpa pernah melangkah. Kita sudah tahu arah yang benar; yang kita perlukan hanyalah kemauan untuk meninggalkan jalan lama. Dan mungkin, sebagaimana setiap perubahan besar dalam sejarah, semuanya akan dimulai bukan dari kampanye kesadaran baru, melainkan dari keberanian sekelompok kecil orang untuk berkata: cukup sudah. Dunia ini tidak bisa diselamatkan dengan terus menumbuhkannya. Dunia hanya bisa diselamatkan dengan belajar berhenti.
* Penggagas Forum Kajian Keutuhan Ciptaan (FKCC) “SEMESTA”
BERITA LAINNYA