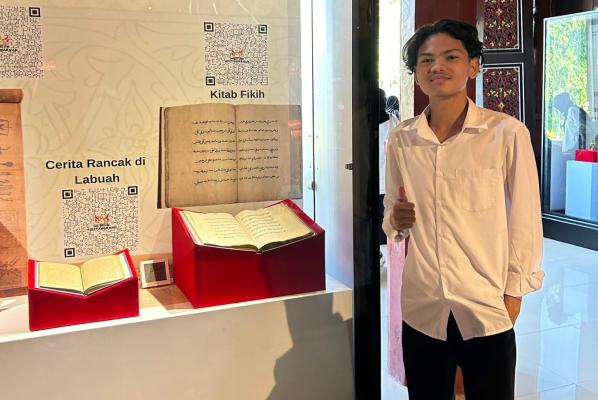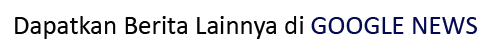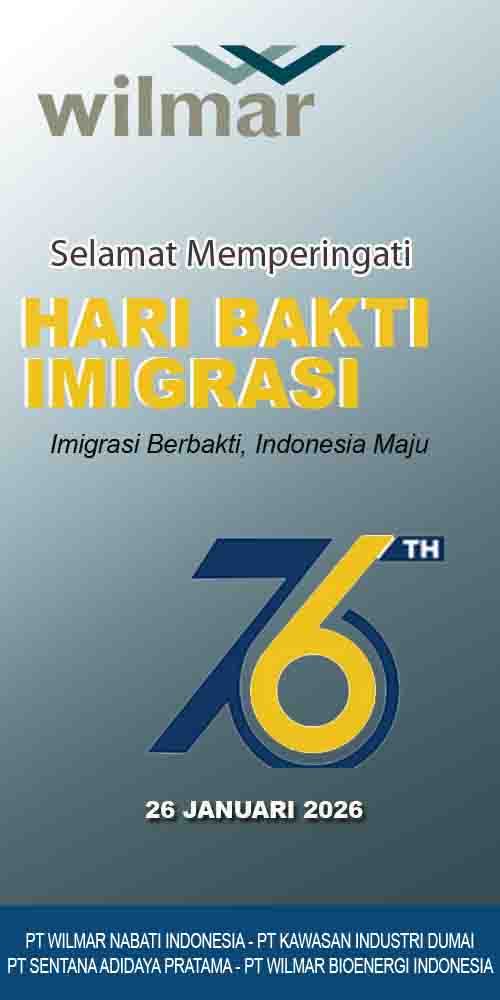- Home
- Ruang Opini
- Menebang Hutan, Menggali Liang Kubur
Menebang Hutan, Menggali Liang Kubur
Oleh: T.H. Hari Sucahyo*

DALAM MITOLOGI Yunani, terdapat kisah yang nyaris tenggelam dalam riuh rendah kisah heroisme dan peperangan para dewa, namun justru menyimpan gema yang paling keras bagi zaman kita: kisah Erysichthon. Sebuah dongeng yang terasa lebih nyata daripada fiksi, lebih relevan dari sekadar mitos purba. Ini bukan sekadar kisah tentang kutukan, melainkan cermin bagi peradaban yang tersesat dalam kerakusan, pemujaan harta, dan penolakan terhadap batas.
Erysichthon bukan raja biasa. Ia adalah personifikasi dari keserakahan yang tak mengenal tepi. Kekayaannya tidak membuatnya bersyukur, kekuasaannya tidak membuatnya bijak. Ia tidak hanya menginginkan lebih; ia menginginkan semua. Keinginannya bukan didasarkan pada kebutuhan, tetapi pada kerakusan murni yang tak lagi mengenal logika. Saat ia memerintahkan penebangan hutan suci milik Ceres dewi bumi, panen, dan kesuburan. Ia tidak sekadar menebang pohon. Ia sedang menghancurkan hubungan paling mendasar antara manusia dan alam: rasa hormat.
Salah satu pohon yang hendak ditebangnya adalah pohon ek tua, yang tak hanya menjadi pusat hutan itu, tetapi juga menjadi tempat bersemayamnya peri penjaga alam. Ketika para pelayannya menolak menebangnya karena ketakutan akan murka ilahi, Erysichthon justru menertawakan mereka. Dengan tangannya sendiri, ia mengayunkan kapak, memotong kehidupan yang telah berakar puluhan bahkan ratusan tahun, dan dalam amarahnya, membunuh sang peri yang mencoba memperingatkannya. Ia menolak mendengar, sebab keserakahan telah menulikan telinganya, membutakan hatinya. Ia tidak bisa membedakan lagi mana yang sakral dan mana yang sekadar sumber eksploitasi.
Di sinilah ironi bermula. Bumi, yang selama ini memberinya kekayaan dan kejayaan, membalas dendam bukan dengan badai atau gempa, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan: kelaparan. Bukan kelaparan biasa, tetapi kelaparan yang menggerogoti dari dalam. Kutukan Ceres tidak datang dalam bentuk halilintar, melainkan dalam bentuk rasa lapar abadi; sebuah metafora yang begitu dalam tentang konsekuensi dari ketamakan.
Erysichthon makan. Dan makan. Dan terus makan. Ia menghabiskan seluruh gudang makanannya dalam satu hari. Lalu dia menjual tanahnya, kemudian ternaknya, lalu rumahnya, dan bahkan putrinya sendiri, Mestra yang, ironisnya, diberi kemampuan oleh dewa untuk berubah bentuk, dan karena itu bisa kembali pada ayahnya setelah dijual. Tapi bahkan keajaiban pun tak bisa menyelamatkan seorang yang telah kehilangan dirinya pada nafsu yang membabi buta.
Sampai akhirnya, setelah seluruh dunia miliknya berubah menjadi debu, yang tersisa hanyalah tubuhnya sendiri. Maka, ia mulai memakan dirinya. Sedikit demi sedikit, dagingnya sendiri menjadi santapan terakhir. Tubuhnya menjadi korban terakhir dari kerakusannya yang tak pernah terpuaskan. Dan di situlah kisah ini mencapai klimaksnya: seorang manusia yang, karena menginginkan segalanya, akhirnya kehilangan segalanya termasuk dirinya sendiri.
Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini' Lebih dari sekadar moral tentang "jangan rakus", Erysichthon adalah simbol dari krisis peradaban modern. Ia adalah gambaran tentang manusia yang memutus tali spiritual dan ekologisnya dengan dunia, demi mengejar kemajuan yang tak terdefinisi. Ia mewakili sistem yang menilai segalanya berdasarkan nilai tukar, yang menjadikan alam sebagai komoditas, dan yang meyakini bahwa pertumbuhan tak mengenal batas.
Kita hidup di zaman di mana hutan-hutan ditebang bukan demi kelangsungan hidup, tetapi demi perluasan proyek real estate mewah. Lautan ditambang bukan demi kebutuhan rakyat banyak, tetapi demi keuntungan investor. Gunung-gunung dikoyak, sungai-sungai dicemari, dan udara dikorbankan di altar industrialisasi yang tak mengenal akhir. Dan ketika krisis datang, apakah itu krisis iklim, krisis pangan, krisis air, krisis identitas, kita seperti Erysichthon yang ketakutan, mencari sesuatu untuk dimakan, namun tak pernah kenyang.
Rasa lapar dalam kisah ini bukan hanya lapar perut, tetapi lapar eksistensial. Lapar akan makna, lapar akan kepuasan batin, lapar akan relasi yang utuh dengan alam, sesama, dan diri sendiri. Erysichthon, dengan kekayaan dan kekuasaannya, tak pernah merasakan kenyang karena ia tak pernah mencicipi kebijaksanaan. Ia tidak tahu batas, dan karena itulah ia tidak tahu arti cukup.
Kisah ini juga menyimpan ironi yang lebih dalam: bahwa rasa lapar itu muncul justru setelah ia menghancurkan sumber pemenuhannya. Hutan suci Ceres adalah simbol dari keterhubungan antara manusia dan alam, tempat segala kebutuhan sebenarnya bisa tercukupi. Tetapi ketika ruang itu dihancurkan demi pemujaan terhadap ego, pemenuhan berubah menjadi kekosongan. Nafsu berubah menjadi lubang hitam yang menelan segala.
Ada pelajaran etis dan spiritual dalam tragedi ini. Dalam berbagai tradisi kebijaksanaan, dari filsafat Timur hingga pemikiran kontemporer, prinsip "cukup" atau moderasi adalah kunci kehidupan yang seimbang. Buddhisme mengenalnya sebagai middle way, Islam mengajarkan wasathiyah, filsafat Stoik menekankan apatheia, dan dalam Kitab Suci pun ada anjuran untuk tidak serakah dan mencintai ciptaan sebagai anugerah, bukan objek eksploitatif. Tetapi Erysichthon mencampakkan semua itu. Ia memilih jalan ekstrem. Dan ekstremitas itulah yang membinasakannya.
Apa jadinya jika dunia ini penuh dengan Erysichthon' Atau, yang lebih menakutkan: bagaimana jika dunia ini sudah penuh dengan Erysichthon' Ketika para pemimpin dan korporat raksasa terus memaksakan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan daya dukung bumi. Ketika masyarakat terus dicekoki budaya konsumsi tanpa batas. Ketika pemenuhan kebutuhan dasar manusia dikorbankan demi gaya hidup yang mewah dan tak berkelanjutan. Maka kita semua sedang berada di jalan yang sama, jalan menuju kehancuran diri sendiri.
Kita bisa melihat kutukan Ceres dalam bentuk yang sangat nyata hari ini. Kekeringan yang melanda wilayah pertanian. Polusi udara yang membunuh diam-diam. Laut yang naik dan mencuri daratan. Penyakit baru yang merebak akibat kehancuran habitat. Bahkan di tengah kemajuan teknologi, masih ada rasa lapar yang tak terpuaskan, bukan hanya lapar fisik, tetapi lapar akan makna, koneksi, dan ketenangan jiwa. Kita, seperti Erysichthon, memakan diri kita sendiri melalui gaya hidup yang merusak dan sistem yang membutakan.
Kisah ini tidak harus berakhir tragis bagi kita. Sebab mitos bukan hanya peringatan, tetapi juga undangan. Ia mengundang kita untuk menyadari kembali batas. Untuk menghormati sakralitas pohon, sungai, dan gunung. Untuk memulihkan hubungan spiritual dengan bumi. Untuk berani mengatakan cukup dalam dunia yang selalu mendorong kita untuk ingin lebih. Untuk tidak malu menjalani hidup yang sederhana, selaras, dan penuh kesadaran.
Erysichthon tidak menyadari bahwa kelimpahan sejati bukanlah tentang akumulasi, tetapi tentang keseimbangan. Ia pikir ia memiliki segalanya, padahal ia tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Dan di sanalah letak kutukan sejati: kehilangan kendali atas diri sendiri karena diperbudak oleh nafsu yang tak pernah terpuaskan.
Dalam dunia yang terus berubah, mungkin pertanyaan yang perlu kita renungkan bukanlah “apa lagi yang bisa kita dapatkan'”, melainkan “apa yang benar-benar kita butuhkan'” Sebab dari sanalah peradaban bisa kembali menemukan arah. Sebab dari sanalah, kita bisa menghindari nasib seperti Erysichthon: ditelan oleh nafsu yang kita cipta sendiri.
_________
*Penulis adalah Penggagas Forum Kajian Keutuhan Ciptaan (FKKC) “SEMESTA”
BERITA LAINNYA